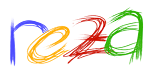Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak anak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlakuan khusus selama proses peradilan.
Tulisan di atas adalah kesimpulan dari jurnal payah ini. Mengenai detailnya akan kami bahas sebagai berikut:
Struktur penulisan tugas jurnal:
- Arial ukuran 11
- Spasi 1,5
- Halaman 15-20
Ketentuan penulisan tugas jurnal:
- Cover (Judul, Nama Anggota, NIM, Fakultas, Tahun)
- Abstrak (dalam Bahasa Indonesia 150-200 kata)
- Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan)
- Tinjauan Pustaka (kerangka teori, konsep, dan regulasi)
- Metode Penulisan (normatif/empiris/kualitatif, dan lain-lain)
- Pembahasan (analisis permasalahan hukum)
- Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka (Chicago Style, minimal 10 pustaka, campuran buku yang maksimal terbit 10 tahun terakhir, jurnal maksimal terbit 5 tahun terakhir, peraturan)
Rumusan Masalah:
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut UU Perlindungan Anak dan UU TPKS?
- Apa saja kendala dalam implementasi pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual?
- Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak anak korban?
Kerangka Teori dan Konsep
a. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan rasa aman kepada warganya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir sebagai alat untuk melindungi dan memanusiakan manusia, bukan sekadar teks peraturan. Perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap pelanggaran hak.
b. Konsep Hak Anak
Hak anak adalah hak asasi yang dimiliki setiap individu di bawah usia 18 tahun. Dalam konteks internasional, hak-hak anak dilindungi oleh Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Hak-hak ini meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam masyarakat.
c. Kekerasan Seksual terhadap Anak
Kekerasan seksual terhadap anak mencakup semua bentuk pelecehan, eksploitasi, pemerkosaan, atau tindakan bernuansa seksual terhadap anak tanpa persetujuan dan melawan kehendaknya. Menurut WHO, kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak yang berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan sosial korban.
Regulasi Terkait
a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 59: Negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual
- Pasal 64: Anak korban berhak memperoleh rehabilitasi, baik medis maupun sosial.
b. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
c. Instrumen lain yang Relevan
- KUHP (Pasal 285, 286, 287 terkait pemerkosaan dan pencabulan),
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak,
- Konvensi Hak Anak (CRC),
- UU No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (jika dikaitkan dengan pelaku anak).
Cover:
HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU TPKS
Chat GPT
000000000
Fakultas Hukum
2025
ABSTRAK
Anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis jangka panjang. Negara telah mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang menyebabkan hak-hak anak korban tidak terpenuhi secara maksimal, baik dari segi hukum, psikososial, maupun institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi solusi untuk optimalisasi perlindungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaanya di lapangan. Oleh karena itu, perlu penguatan implementasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemenuhan layanan pendampingan terpadu bagi korban.
Kata kunci: hak anak, kekerasan seksual, perlindungan hukum, UU Perlindungan Anak, UU TPKS
1. Pendahuluan:
Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam tahap tumbuh kembangnya, anak berada dalam posisi rentan yang memerlukan perlindungan khusus, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan ini menjadi semakin penting ketika anak menjadi korban kekerasan seksual—sebuah tindakan pidana yang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan dan integritas psikologis anak sebagai individu.
Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai lembaga pemerhati anak mencatat bahwa kasus kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling sering dilaporkan. Yang lebih tragis, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga, guru, atau tetangga, yang seharusnya berperan sebagai pelindung.
Negara melalui kerangka hukum positif telah mengatur berbagai instrumen perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dua instrumen utama yang menjadi pijakan penting adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini memberikan pendampingan hukum, hak atas rehabilitasi, dan keharusan negara untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi korban.
Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala serius. Banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang layak. Tidak sedikit pula kasus yang berujung pada penghentian penyidikan karena minimnya bukti atau keberpihakan sistem hukum terhadap pelaku. Implementasi undang-undang sering kali terhambat oleh keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban anak.
Melalui tulisan ini, penulis berupaya menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, serta menelaah hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas regulasi yang ada, sekaligus menawarkan refleksi terhadap langkah-langkah yang perlu diperkuat untuk memastikan terpenuhinya hak anak korban secara menyeluruh dan berkeadilan.
2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan.
Pendekatan normatif digunakan karena permasalahan utama dalam tulisan ini menyangkut analisis terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup studi literatur yang bersumber dari:
- Undang-undang,
- Peraturan pemerintah,
- Buku teks hukum,
- Artikel jurnal hukum,
- Laporan lembaga resmi,
- Sumber sekunder lainnya yang relevan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menginterpretasikan isi norma hukum dan membandingkannya dengan praktik di lapangan, sehingga diperoleh kesimpulan secara deskriptif-analitis.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat secara normatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak atas perlindungan khusus. Pasal 59 ayat (2) huruf j menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat:
- Perlindungan hukum,
- Pendampingan psikologis,
- Rehabilitasi medis dan sosial,
- Jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa.
Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat aspek perlindungan korban dengan menciptakan sistem yang lebih menyeluruh, mencakup:
- Pemulihan korban,
- Pemenuhan hak atas informasi, perlindungan, dan bantuan hukum,
- Layanan rumah aman, konseling, dan bantuan psikososial.
UU TPKS secara eksplisit menyebut anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlakuan berbeda dan lebih khusus, dengan pendekatan trauma healing dan layanan yang terintegrasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum.
Selain itu, beberapa kebijakan lain seperti PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, dan pedoman dari KPAI serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memberikan landasan pelaksanaan di lapangan. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) juga memberi kemungkinan mekanisme khusus jika pelaku adalah anak.
b. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum
Meskipun instrumen hukum sudah cukup komprehensif, pelaksanaan di lapangan menghadapi banyak kendala, antara lain:
1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dan Aparat
Banyak aparat penegak hukum dan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya isi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Hal ini menyebabkan pendekatan terhadap korban sering kali tidak berpihak, bahkan menyalahkan korban (victim blaming).
2) Minimnya Layanan Pendamping Terpadu
Layanan seperti konseling psikologis, shelter, dan bantuan hukum masih terbatas, terutama di daerah. Banyak korban tidak tahu harus mengadu ke mana, dan ketika mengadu, prosesnya lambat atau tidak responsif.
3) Stigma Sosial terhadap Korban
Anak korban kekerasan seksual dan keluarganya kerap mendapatkan tekanan sosial, dianggap "memalukan", sehingga kasus tidak dilaporkan atau dihentikan sebelum masuk ke proses hukum.
4) Kurangya Koordinasi antar Lembaga
Pelaksanaan perlindungan anak melibatkan banyak pihak: kepolisian, kejaksaan, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), psikologi, dan lembaga sosial. Koordinasi yang lemah membuat proses pendampingan menjadi tidak optimal atau bahkan terputus.
5) Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Banyak daerah tidak memiliki tenaga profesional seperti psikologi anak, pekerja sosial, atau advokat yang khusus menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anggaran untuk pelatihan juga terbatas.
c. Upaya Penguatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa langkah penguatan yang dapat direkomendasikan antara lain:
- Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif korban dan anak
- Peningkatan layanan pemulihan korban yang mudah diakses dan ramah anak.
- Pembuatan SOP terpadu antar lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual anak agar tidak tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab.
- Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi dan mendampingi korban, bukan malah menyalahkan.
- Perluasan layanan hukum gratis melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau universitas.
4. Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak anak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlakuan khusus selama proses peradilan.
Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala serius. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan layanan pendampingan yang ramah anak, minimnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma terhadap korban menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan realitas pelaksanaan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.
Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan yang berperspektif korban. Layanan pemulihan korban harus diperluas, terutama di daerah, dengan menyediakan shelter, bantuan psikososial, dan pendampingan hukum secara gratis. Di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi agar tidak lagi melakukan stigma terhadap korban, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan yang aktif. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, psikolo, dan pendamping sosial juga harus diperkuat melalui prosedur operasional standar yang jelas dan terintegrasi.
Dengan sinergi antara regulasi yang kuat dan implementasi yang responsif, hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilindungi secara nyata, sehingga mereka dapat pulih dan tumbuh kembali sebagai individu yang utuh dan berdaya.
5. Daftar Pustaka
Gunarto, Gunarto. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
Rahardji, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM, 2014.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
Fitria, Rahma. "Evaluasi Implementasi UU TPKS terhadap Penanganan Korban Anak." Jurnal HAM, vol. 14, no. 1 (2022): 80-95.
Lestari, Maria. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Yuridis dan Psikologis." Jurnal Mimbar Hukum, vol. 35, no. 1 (2023): 45-60.
Nugroho, Arif Budi. "Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Anak." Jurnal Hukum Responsif, vol. 8, No. 2 (2022): 123-135.
Sari, Dwi Ratna, dan Fajriyah Maulida. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU Perlindungan Anak dan UU TPKS." Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, vol. 5, No. 1 (2023): 55-70.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan Tahunan KPAI 2022: Perlindungan Anak dalam Ancaman Kekerasan Seksual. Jakarta: KPAI, 2023.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Panduan Perlindungan Korban Anak Kekerasan Seksual. Jakarta: LPSK, 2022.
Unduh file: (drive.google.com)